ABSTRAK
Menanggapi meningkatnya konflik atas sumber daya alam, seperti mineral, beberapa negara, termasuk Swedia, telah beralih ke praktik demokrasi musyawarah sebagai sarana tata kelola. Namun, meskipun ada upaya signifikan untuk memasukkan unsur musyawarah ke dalam sistem tata kelola pertambangan Swedia, sistem tersebut gagal memenuhi janji yang biasanya dikaitkan dengan demokrasi musyawarah, seperti manajemen konflik yang efektif. Makalah ini mengeksplorasi paradoks ini dengan meneliti bagaimana musyawarah telah diterapkan dalam desain kelembagaan sistem dan mengevaluasi sejauh mana ia mendorong kondisi yang kondusif untuk musyawarah yang selaras dengan cita-cita demokrasi musyawarah. Temuan tersebut mengungkapkan perluasan praktik musyawarah yang nyata dalam desain kelembagaan, khususnya melalui ketentuan yang mengharuskan konsultasi dan dialog dengan para aktor yang terkena dampak pertambangan dan kegiatan terkait. Namun, masih ada kekurangan substansial, terutama mengenai mekanisme pemilihan peserta, resep untuk interaksi peserta, dan hubungan antara interaksi ini dan pengambilan keputusan. Kekurangan ini menghambat realisasi musyawarah yang ideal, menawarkan penjelasan yang meyakinkan untuk kesulitan sistem dalam mengelola konflik yang meningkat. Menanggapi tantangan ini, penelitian ini merekomendasikan reformasi kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi sistem. Lebih jauh, penelitian ini menyoroti perlunya penelitian di masa mendatang untuk menyelidiki berbagai desain kelembagaan dan dampaknya terhadap musyawarah dalam berbagai sistem tata kelola. Penelitian semacam itu dapat menjelaskan bagaimana desain ini memfasilitasi atau menghalangi musyawarah yang efektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan demokrasi dan kemampuan sistem tata kelola untuk mengatasi konflik sumber daya alam yang meningkat.
1 Pendahuluan
Kekokohan sistem demokrasi kita terkait erat dengan kapasitasnya untuk menghasilkan keputusan yang sah dalam menghadapi ketidaksepakatan publik (Curato et al. 2017; Rein dan Schön 1996). Namun, seiring meningkatnya persaingan untuk sumber daya alam, hal itu telah menimbulkan konflik yang sulit diatasi yang sering kali menggagalkan upaya untuk mencapai keputusan tersebut (Bebbington dan Humphreys Bebbington 2018; Beland Lindahl et al. 2018).
Cara mengatasi konflik yang sulit diatasi merupakan subjek perdebatan yang luas, dengan para akademisi menganjurkan berbagai pendekatan (Mouffe 1999; Rein dan Schön 1996). Sejak dimulainya pada tahun 1980-an, demokrasi deliberatif telah muncul sebagai kerangka teoritis yang menonjol dan berpengaruh dalam perdebatan ini, memainkan peran penting dalam membentuk praktik demokrasi saat ini dan menginformasikan pendekatan terhadap tata kelola sumber daya alam (Bäckstrand et al. 2010; Johansson et al. 2022). Demokrasi deliberatif adalah teori normatif yang menempatkan diskusi yang inklusif, setara, dan beralasan (yaitu, musyawarah) antara para aktor yang terdampak di jantung pengambilan keputusan yang sah (Bächtiger et al. 2018a; Willis et al. 2022). Meskipun teori ini sering diperjuangkan karena nilai normatifnya yang inheren, adopsi yang luas terutama dapat dikaitkan dengan potensinya untuk menghasilkan berbagai hasil, termasuk manajemen konflik yang efektif (lihat Kuyper 2018 untuk tinjauan hasil). Secara khusus, dijanjikan bahwa semakin besar tingkat pengambilan keputusan sistem tata kelola yang diinformasikan oleh musyawarah yang inklusif dan autentik (yaitu, semakin tinggi kapasitas musyawarahnya), semakin efektif pula sistem tersebut dalam mencapai keputusan yang sah dalam menghadapi konflik publik (Bächtiger et al. 2018a; Bäckstrand et al. 2010; Curato et al. 2017). Hal ini, menurut teori tersebut, karena musyawarah autentik, di mana para peserta terlibat sepenuhnya dan sungguh-sungguh dengan semua aspek relevan dari suatu isu, kondusif untuk kesepakatan yang diterima bersama atau, ketika kesepakatan tidak dapat dicapai, membantu memperjelas konflik, yang darinya keputusan atau hasil yang dapat diterima secara luas dapat diturunkan, misalnya, melalui prosedur agregatif (Curato et al. 2017; Dryzek dan Niemeyer 2010). Sejak tahun 1980-an, Negara Swedia telah melakukan upaya signifikan untuk mengintegrasikan unsur-unsur musyawarah ke dalam semua proses pengambilan keputusan mengenai kebolehan penambangan dan kegiatan terkait (Pölönen et al. 2020). Ledakan pertambangan di awal tahun 2000-an dan eskalasi konflik penggunaan lahan berikutnya semakin menekankan pentingnya musyawarah dalam keputusan yang terkait dengan pertambangan (Beland Lindahl et al. 2018; Johansson et al. 2022; Johansson 2023). Tujuan yang dinyatakan di balik pendekatan ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, meningkatkan pengelolaan kepentingan penggunaan lahan yang bersaing, dan mengurangi atau mencegah konflik dan banding (Pölönen et al. 2020; Kementerian Perusahaan, Energi, dan Komunikasi Swedia 2013).
Adalah wajar untuk mengantisipasi bahwa penerapan dan perluasan unsur-unsur musyawarah akan meningkatkan kemampuan sistem tata kelola pertambangan Swedia untuk mengelola trade-off dan menghasilkan keputusan yang lebih sah.
Penelitian sebelumnya tentang tata kelola pertambangan Swedia menyoroti beberapa kelemahan sistemik yang menyebabkan konflik meningkat atau terus berlanjut, termasuk: tujuan kebijakan yang sempit (Haikola dan Anshelm 2016); meningkatnya ketergantungan pada langkah-langkah kebijakan pasar-liberal (Haikola dan Anshelm 2018); distribusi dampak dan manfaat yang tidak merata (Poelzer et al. 2020); undang-undang yang tidak jelas (Poelzer et al. 2021); lembaga yang terkoordinasi dengan lemah (Poelzer et al. 2020); kesempatan yang tidak adil untuk berpartisipasi dan memengaruhi dalam proses perizinan (Fjellborg 2023; Johansson 2023); dan tingkat pengakuan yang lemah terhadap hak-hak Masyarakat Adat Sami (Raitio et al. 2020). Namun, penelitian tentang elemen-elemen deliberatif dari sistem tersebut masih tertinggal (Pölönen et al. 2020). Penelitian musyawarah hingga saat ini sebagian besar berfokus pada dampak musyawarah dalam eksperimen atau forum musyawarah skala kecil, di mana sampel representatif warga negara ditugaskan untuk berunding tentang isu-isu yang disengketakan dengan sedikit atau tanpa kekuatan pengambilan keputusan (lihat Bächtiger dan Parkinson 2019; Kuyper 2018 dan Willis et al. 2022 untuk tinjauan terkini). Meskipun berharga dalam menjelaskan potensi hasil komunikasi musyawarah, penelitian ini tidak dapat menjelaskan implementasi dan fungsi musyawarah dalam sistem tata kelola dunia nyata, dan memberikan sedikit panduan untuk meningkatkan fungsi sistem ini.
Penelitian dalam bidang seperti tata kelola kolaboratif dan demokrasi partisipatif menyoroti mengapa musyawarah sering kali gagal dalam pengaturan dunia nyata (Armeni dan Lee 2021; Baker dan Chapin III 2018). Temuan umum adalah bahwa proses musyawarah sering kali sesuai dengan kerangka kelembagaan yang sudah ada sebelumnya, yang membatasi keberagaman peserta, membatasi topik musyawarah, dan mengurangi kekuatan pengambilan keputusan dari proses ini (Arai et al. 2021; Raitio 2013). Hal ini sering kali menghasilkan proses tokenistik yang memperkuat status quo (Bäckstrand et al. 2010; Williams et al. 2022). Oleh karena itu, mengevaluasi kapasitas demokrasi suatu sistem memerlukan pertimbangan terhadap kendala yang diberlakukan oleh desain kelembagaannya (Castro 2020).
Menanggapi teka-teki dan kesenjangan penelitian yang disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana musyawarah diterapkan dalam desain kelembagaan sistem tata kelola pertambangan Swedia, serta menilai sejauh mana desain tersebut menciptakan kondisi untuk musyawarah yang mematuhi prinsip-prinsip demokrasi musyawarah. Untuk mencapai hal ini, penelitian ini menggunakan analisis tematik kualitatif dari kerangka peraturan formal yang mengatur perizinan pertambangan di Swedia, dengan mengacu pada kerangka pengembangan kapasitas musyawarah John Dryzek (Dryzek 2009).
Studi ini menawarkan kontribusi di berbagai bidang, karena menghasilkan pengetahuan empiris yang penting tentang aspek musyawarah dalam sistem tata kelola pertambangan Swedia dan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana demokrasi musyawarah diwujudkan dan dioperasionalkan dalam tata kelola sumber daya alam di dunia nyata. Hal ini memperluas pemahaman terkini tentang fungsi demokrasi musyawarah di luar forum skala kecil sekaligus menyoroti tantangan yang terlibat dalam mengintegrasikan musyawarah ke dalam konteks tata kelola praktis. Selain itu, studi ini memberikan temuan kebijakan yang relevan dan berharga yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan sistem tata kelola yang ada yang relevan tidak hanya dengan tata kelola pertambangan Swedia tetapi juga dengan sistem lain yang sebanding.
2 Teori
2.1 Demokrasi Deliberatif dan Standar Aspiratifnya
Demokrasi deliberatif adalah teori politik normatif yang mempromosikan cita-cita di mana semua pihak yang terpengaruh oleh suatu keputusan berkumpul bersama dalam kondisi yang setara dan adil untuk membahas isu-isu yang mereka hadapi dan, atas dasar diskusi tersebut, memutuskan kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan mereka (Bächtiger et al. 2018a). Cita-cita tersebut telah mengalami perkembangan dan revisi yang signifikan selama bertahun-tahun mengikuti berbagai gelombang perdebatan normatif dan penelitian empiris (Elstub et al. 2016). Ada juga berbagai varian cita-cita tersebut (lihat misalnya, Bächtiger et al. 2010). Dalam studi ini, kerangka kerja pengembangan kapasitas deliberatif Dryzek (2009) diadopsi, di mana cita-cita tersebut didefinisikan sebagai sistem politik yang mempromosikan musyawarah tentang masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama, yang memenuhi kriteria inklusivitas, keaslian, dan konsekuensialitas. Tingkat keselarasan sistem tata kelola dengan kriteria ini menentukan kapasitas musyawarahnya.
Inklusivitas mengacu pada prinsip demokrasi yang melibatkan semua pihak, yaitu, semua pihak yang terpengaruh oleh keputusan atau hasil kolektif harus memiliki kesempatan untuk memberikan masukan (Curato et al. 2019; Dryzek 2009). Oleh karena itu, agar musyawarah bersifat inklusif, semua aktor yang terpengaruh (atau perwakilan mereka) harus diberi kesempatan dan kemampuan untuk berunding tentang isi keputusan/hasil. Kriteria tersebut dapat diterapkan secara berbeda tergantung pada situasi dan jenis inklusi yang memungkinkan: Kriteria tersebut dapat berarti inklusi individu, kelompok, kepentingan, atau wacana/perspektif yang ada dalam lingkungan politik (Dryzek 2009).
Keaslian menyangkut kualitas musyawarah (Dryzek 2009). Secara minimal, musyawarah memerlukan ‘komunikasi bersama yang melibatkan pertimbangan dan refleksi atas preferensi, nilai, dan kepentingan terkait masalah yang menjadi perhatian bersama’ (Bächtiger et al. 2018b, 2). Musyawarah dapat mengambil bentuk yang berbeda tergantung pada tujuan dan konteks, dan kriteria yang berbeda dapat diterapkan. Namun, musyawarah yang autentik terjadi ketika para peserta terlibat dalam proses yang adil, berusaha meyakinkan satu sama lain untuk menerima perspektif dan/atau preferensi tertentu melalui pertukaran alasan secara timbal balik, termasuk mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menggunakan taktik yang memaksa atau manipulatif (Bächtiger dan Parkinson 2019; Curato et al. 2019). Berbagai bentuk pemberian alasan diperbolehkan untuk memastikan bahwa komunikasi yang inklusif dan bermakna dapat terjadi di antara berbagai kelompok, namun para peserta harus mengomunikasikan alasan mereka dalam istilah yang dapat diterima oleh orang lain (Dryzek 2009).
Terakhir, konsekuensialitas menyangkut hubungan antara musyawarah dan keputusan atau hasil kolektif (Dryzek 2009). Agar memiliki konsekuensi, musyawarah harus berdampak pada keputusan/hasil kolektif (Bächtiger et al. 2018a). Dampak ini tidak harus langsung, dan mekanisme yang menerjemahkan hasil musyawarah menjadi keputusan dapat bervariasi, tetapi penting bahwa hasil musyawarah, khususnya preferensi (yang diubah) dan alasan yang berlaku dalam proses, tercermin dalam isi keputusan/hasil (Dryzek 2009).
Setelah menguraikan cita-cita demokrasi musyawarah dan standarnya, bagian selanjutnya mengeksplorasi teori kelembagaan untuk menghubungkan lembaga dengan musyawarah dan memperkenalkan kerangka analitis untuk menilai sejauh mana desain kelembagaan mendorong musyawarah yang inklusif, autentik, dan konsekuensial
2.2 Desain Kelembagaan dan Kapasitas Musyawarah
Kelembagaan adalah aturan dan norma yang ditetapkan dan diakui yang membentuk dan mengatur tindakan dalam berbagai situasi (Hay 2002). Kelembagaan dapat muncul secara spontan melalui interaksi sosial atau sengaja diciptakan melalui pembuatan kebijakan dan proses musyawarah lainnya, dengan studi ini berfokus pada yang terakhir di bawah istilah desain kelembagaan.
Kelembagaan menginformasikan tindakan dengan menyediakan kerangka kerja khusus untuk interpretasi dan tindakan (sementara meminggirkan/mengecualikan alternatif) yang mendefinisikan dan mendikte situasi yang dihadapi; aktor, peran dan hubungan yang terlibat; dan perilaku atau tindakan yang diharapkan dari para aktor (Berger dan Luckmann 1966; Weber dan Glynn 2006). Kerangka kerja ini diwujudkan dan ditegakkan melalui berbagai mekanisme sosial, seperti internalisasi, sosialisasi, sanksi, penghargaan dan pengawasan sosial (Hay 2002).
Penting untuk dicatat bahwa lembaga tidak secara ketat mendikte tindakan. Aktor selalu memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan menanggapi lingkungan sosial mereka (Sass dan Dryzek 2014; Wagenaar 2011; Weber dan Glynn 2006). Selain itu, lembaga hanyalah salah satu dari banyak faktor yang memengaruhi musyawarah (Dryzek 2009). Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa ketika tindakan dan interaksi terjadi dalam sistem tata kelola formal, rancangan kelembagaan—yang diperkuat oleh lembaga publik—memainkan peran yang menentukan dalam membentuknya (Castro 2020; Williams et al. 2022). Oleh karena itu, rancangan kelembagaan sangat penting dan berfungsi sebagai indikator utama untuk mengevaluasi kualitas musyawarah suatu sistem tata kelola.
Dengan mengintegrasikan kerangka kerja pengembangan kapasitas musyawarah dengan teori kelembagaan, kerangka kerja analitis dapat dibangun (lihat Tabel 1). Kerangka kerja ini berfokus pada tiga dimensi kelembagaan yang sesuai dengan kriteria musyawarah (lihat Castro 2020 untuk penjelasan yang lebih mendalam): (1) mekanisme untuk pemilihan peserta, (2) resep untuk interaksi peserta dan (3) hubungan antara interaksi peserta dan pengambilan keputusan. Untuk menciptakan kondisi bagi musyawarah yang inklusif, desain kelembagaan harus menetapkan mekanisme pemilihan peserta yang memastikan kesempatan dan kemampuan bagi spektrum luas aktor yang terkena dampak untuk berpartisipasi, yang mencakup beragam perspektif. Untuk menciptakan kondisi bagi musyawarah yang autentik, desain harus meresepkan bentuk-bentuk interaksi yang memfasilitasi komunikasi timbal balik dan memastikan kesempatan yang sama bagi peserta untuk mengekspresikan preferensi dan alasan mereka. Akhirnya, untuk menciptakan kondisi bagi musyawarah konsekuensial, desain kelembagaan harus menyusun hubungan antara interaksi peserta dan pengambilan keputusan dengan cara yang memungkinkan hasil musyawarah berdampak pada keputusan kritis.
3 Metode
Analisis melibatkan kombinasi analisis dokumen dan analisis tematik kualitatif (Spencer et al. 2014) yang diterapkan pada kerangka regulasi sistem perizinan pertambangan Swedia. Sistem ini mencakup lima proses perizinan yang berbeda, seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 1. Proses ini meliputi (1) proses perizinan eksplorasi yang diatur oleh Undang-Undang Mineral (1991:45), (2) proses perizinan pertambangan yang diatur oleh Undang-Undang Mineral, (3) proses perizinan lingkungan yang diatur oleh Kode Lingkungan (1998:808), (4) pengambilalihan tanah yang diatur oleh Undang-Undang Mineral, dan (5) proses perizinan bangunan yang diatur oleh Undang-Undang Perencanaan
4 Hasil
Hasil tersebut disusun menjadi dua bagian, yang sejalan dengan tujuan penelitian. Bagian pertama menyajikan bagaimana musyawarah dilaksanakan dalam desain kelembagaan sistem tata kelola pertambangan Swedia, yang mencakup ketentuan yang berkaitan dengan proses izin eksplorasi, izin pertambangan, dan izin lingkungan. Bagian kedua menyajikan sejauh mana desain kelembagaan menetapkan kondisi untuk musyawarah yang mematuhi standar demokrasi musyawarah.
4.1 Elemen-elemen Deliberatif dari Sistem Tata Kelola Pertambangan Swedia
4.1.1 Izin Eksplorasi
Izin eksplorasi, yang diberikan oleh Inspektorat Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Mineral (pasal 8, s. 1), memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mencari dan menyelidiki mineral di area yang ditentukan dan hak istimewa untuk mendapatkan izin pertambangan di area tersebut (pasal 3, s. 1).1 Izin eksplorasi memiliki durasi 3 tahun, dengan kemungkinan tiga kali perpanjangan, dengan total maksimum 9 tahun jika ‘alasan penting’ diberikan oleh pemohon (pasal 2, ss. 5–7).
Tujuan dari ketentuan izin ini adalah untuk mendorong eksplorasi yang luas di seluruh negeri, memastikan bahwa eksplorasi dapat dilakukan di area mana pun dengan potensi endapan mineral, terlepas dari kepemilikan tanah dan dengan sedikit batasan (Prop. 1992/93:238, 1). Untuk memfasilitasi hal ini, persyaratan untuk memperoleh izin ditetapkan pada ambang batas yang rendah, yang mensyaratkan (1) niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan eksplorasi, (2) tidak ada ketidaksesuaian sebelumnya untuk eksplorasi, dan (3) harapan yang wajar untuk menemukan mineral konsesi (UU Mineral, bab 2, s. 2).
Proses izin eksplorasi memberlakukan pembatasan yang signifikan terhadap partisipasi. Inspektorat Pertambangan dapat menilai apakah persyaratan terpenuhi dan memberikan izin eksplorasi tanpa masukan dari aktor yang terdampak, dengan kesempatan formal untuk memberikan komentar terbatas pada Dewan Administratif Daerah (CAB) yang relevan,2 kotamadya, dan, jika area izin digunakan oleh masyarakat penggembala rusa kutub (RHC) Sami Pribumi,3 Parlemen Sami (UU Mineral, s. 3). Aktor yang terdampak, termasuk pemilik properti dan pemegang hak lainnya, hanya dijamin pemberitahuan tentang permohonan dan hak untuk mengajukan banding jika mereka dapat menunjukkan bahwa keputusan tersebut memengaruhi hak atau kepentingan mereka (UU Mineral, s. 3; UU Mineral, bab 16, s. 1). Batasan-batasan ini dibenarkan oleh klaim bahwa aktivitas eksplorasi menyebabkan kerusakan sementara yang minimal, bahwa ketentuan kompensasi mengurangi risiko bagi pelaku yang tidak dapat menyampaikan pandangan mereka, bahwa masukan yang berarti dari para pelaku ini tidak mungkin, dan bahwa komunikasi awal akan meningkatkan beban kerja dan menunda proses secara tidak perlu (Prop. 2004/05:40, 42–43).
Meskipun ada batasan-batasan ini, proses perizinan eksplorasi mencakup beberapa elemen musyawarah, khususnya dalam aturan pengembangan rencana kerja (Minerals Act, bab 3, s. 5). Prosedur rencana kerja diperkenalkan pada tahun 2005 untuk mengatasi kritik publik terhadap Minerals Act, yang dianggap ketinggalan zaman dan tidak adil selama ledakan pertambangan awal tahun 2000-an (Prop. 2004/05:40, 30, 60–61). Prosedur ini bertujuan untuk membangun dialog awal, transparan, dan efektif antara para prospektor dan pelaku yang terdampak selama eksplorasi, meningkatkan arus informasi, meningkatkan peluang untuk memengaruhi aktivitas eksplorasi, dan mencegah perselisihan (Prop. 2004/05:40, 50–51).
Prosedur tersebut mengharuskan pemegang izin untuk berkonsultasi dengan para pelaku yang secara langsung terkena dampak eksplorasi, termasuk pemilik properti dan pemegang hak, untuk membuat rencana kegiatan eksplorasi (UU Mineral, bab 3, s. 5). Rencana tersebut harus mencakup aspek-aspek seperti metode eksplorasi, jadwal kerja, langkah-langkah untuk kompensasi kerusakan, dan penilaian dampak terhadap kepentingan publik dan swasta (bab 3, s. 5). Setelah selesai, rencana tersebut harus dikirimkan kepada para pelaku secara tertulis, dengan jangka waktu 3 minggu untuk mengajukan keberatan (UU Mineral, s. 9 a). dan Pembangunan (2010:900). Fokus analisis adalah pada ketentuan yang mTidak ada persyaratan formal yang mewajibkan penggunaan metode musyawarah dalam mengembangkan rencana kerja, yang memberikan kebebasan kepada pemegang izin untuk menentukan tingkat dan bentuk keterlibatan. Namun, Undang-Undang Mineral memberi insentif pada dialog yang mencari konsensus dengan mengizinkan rencana kerja berlaku segera, melewati tinjauan lembaga, jika kesepakatan bersama dicapai antara pemegang izin dan pelaku yang terdampak (yaitu, jika tidak ada keberatan terhadap rencana tersebut atau jika pemegang izin mencapai kesepakatan dengan pelaku yang keberatan) (Undang-Undang Mineral, bab 3, s. 5 c; Prop. 2004/05:40, 50–53). Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, pemegang izin harus meminta tinjauan dan validasi rencana oleh Inspektorat Pertambangan, yang memperpanjang jangka waktu. Banding terhadap validasi Inspektorat Pertambangan ditangani oleh Pengadilan Tanah dan Lingkungan (LEC). Khususnya, kegiatan eksplorasi tidak dapat dihentikan selama prosedur rencana kerja, karena keputusan izin sebelumnya telah mengonfirmasi pemenuhan persyaratan eksplorasi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Konsultasi Sami (2022:66), Inspektorat Pertambangan harus selalu berkonsultasi dengan perwakilan Sami, termasuk Parlemen Sami dan RHC yang terdampak, sebelum memvalidasi rencana kerja yang berdampak pada hak dan kepentingan Sami (pasal 2 dan 7). Konsultasi ini harus dilakukan dengan itikad baik, dengan mempertimbangkan preferensi Sami, dengan peserta diharapkan untuk menyampaikan posisi yang beralasan dan mempertimbangkan pandangan satu sama lain (pasal 9 dan 11). Proses ini berlanjut hingga kesepakatan tercapai atau dianggap tidak dapat dicapai, setelah itu Inspektorat Pertambangan memvalidasi rencana dan memberlakukan persyaratan yang diperlukan (pasal 11). Yang penting, Undang-Undang tersebut hanya memberlakukan kewajiban prosedural dan tidak mengubah hukum substantif, sehingga persetujuan Sami bukanlah persyaratan.4
4.1.2 Izin Pertambangan
Jika endapan mineral yang layak secara ekonomi diidentifikasi, izin pertambangan dapat diajukan. Seperti izin eksplorasi, Inspektorat Pertambangan, berdasarkan Undang-Undang Mineral, memberikan izin pertambangan, yang memberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi mineral di dalam area yang ditentukan (Undang-Undang Mineral, bab 5, bagian 1; bab, 8 bagian 1). Izin tersebut tidak mengizinkan aktivitas pertambangan, yang memerlukan izin lingkungan dan bangunan yang terpisah, tetapi memperoleh izin pertambangan merupakan prasyarat untuk keduanya (Prop. 1988/89:92, 46). Selain itu, proses izin pertambangan menentukan apakah pertambangan harus didahulukan daripada penggunaan lahan lainnya, keputusan yang mengikat dalam proses izin lingkungan berikutnya. Oleh karena itu, izin pertambangan secara kuat menunjukkan kebolehan keseluruhan suatu proyek. Izin pertambangan awalnya berlaku selama 25 tahun tetapi dapat diperpanjang untuk periode tambahan 10 tahun jika ada aktivitas yang sedang berlangsung atau jika dianggap demi kepentingan umum untuk mengeksploitasi endapan mineral (bab 4, bagian 7–10). Seperti ketentuan izin eksplorasi, syarat-syarat yang menguntungkan ditetapkan untuk pemberian izin pertambangan dengan tujuan memfasilitasi eksploitasi endapan mineral secara ekstensif. Secara khusus, izin harus diberikan jika (1) endapan tersebut kemungkinan besar layak secara ekonomi, (2) lokasi dan sifat endapan tersebut tidak membuat ekstraksi menjadi tidak tepat dan (3) izin tersebut tidak bertentangan dengan rencana tata guna lahan kota atau peraturan daerah (Undang-Undang Mineral, bab 4, s. 2). Untuk mengevaluasi apakah syarat-syarat ini terpenuhi, Inspektorat Pertambangan meninjau permohonan dan berkonsultasi dengan CAB yang relevan, yang menyeimbangkan kepentingan publik dalam eksploitasi mineral dengan kepentingan publik lainnya yang terkait dengan lokasi, berdasarkan penilaian dampak lingkungan (EIA) pemohon yang diwajibkan dalam permohonan (bab 8, s. 1). Penyeimbangan kepentingan publik oleh CAB harus menilai apakah koeksistensi dimungkinkan dan, jika tidak, memprioritaskan kepentingan yang paling mendukung pembangunan berkelanjutan (Kode Lingkungan, bab 3–4; Prop. 1997/98:45). Sifat ketentuan yang luas dan fleksibel ini memungkinkan penyesuaian terhadap berbagai situasi dan pertimbangan politik, sehingga memberikan kewenangan yang cukup besar kepada CAB. Penilaian CAB harus menjadi panduan bagi keputusan perizinan Inspektorat Pertambangan. Namun, jika Inspektorat Pertambangan tidak setuju atau menganggap masalah tersebut sebagai kepentingan publik yang luar biasa, maka Inspektorat dapat merujuk masalah tersebut kepada Pemerintah, sehingga keputusan dapat disesuaikan dengan agenda politik nasional (UU Pertambangan, bab 8, s. 2).engatur tiga proses pertama, karena di situlah keputusan terkait dengan izin pertambangan dibuat (Raitio et al. 2020).
Proses perizinan pertambangan menawarkan lebih banyak peluang untuk berpartisipasi daripada proses perizinan eksplorasi. Pemilik properti dan pemegang hak memiliki waktu 4 minggu untuk menyampaikan pendapat dan keberatan terkait permohonan perizinan dan AMDAL (Peraturan Daerah Pertambangan, pasal 21). Kotamadya yang terdampak juga dapat memberikan masukan selama penilaian kepentingan publik oleh Badan Penilai (pasal 28). Selain itu, Inspektorat Pertambangan harus berkonsultasi dengan perwakilan Masyarakat Adat Sami, termasuk Parlemen Sami dan RHC yang terdampak, jika izin pertambangan berdampak pada hak dan kepentingan mereka, sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Konsultasi Sami. Peluang untuk mengajukan banding juga tersedia, dengan Pemerintah menangani banding atas keputusan Inspektorat Pertambangan, memberikan kedudukan hukum kepada mereka yang terdampak langsung, termasuk kotamadya dan organisasi lingkungan (Undang-Undang Pertambangan, bab 16, pasal 1, 4). Banding terhadap keputusan pemerintah ditinjau oleh Mahkamah Tata Usaha Agung, yang menilai kesalahan prosedural atau penyalahgunaan wewenang tetapi tidak mengevaluasi substansi keputusan (Undang-Undang 2006:304).
Elemen-elemen pertimbangan dalam peraturan yang mengatur proses perizinan pertambangan terutama ditemukan dalam ketentuan-ketentuan AMDAL Kode Lingkungan, yang mulai berlaku ketika pemohon mengembangkan AMDAL yang berfungsi sebagai dasar bagi penyeimbangan kepentingan publik oleh CAB (Kode Lingkungan, bab 6, bagian 29–32). Ketentuan AMDAL dalam Kode Lingkungan (bab 6) berakar pada Arahan AMDAL UE (2014) (2011/92/EU, amend. 2014/52/EU) dan Konvensi Espoo (1991) dan Konvensi Aarhus (1998). AMDAL berfungsi sebagai alat perencanaan pertimbangan dengan tiga tujuan utama: menggabungkan pertimbangan lingkungan yang relevan ke dalam pengambilan keputusan, memastikan akses publik terhadap informasi lingkungan, dan mendorong partisipasi dan dialog publik dalam pengambilan keputusan lingkungan (Prop. 2016/17:200, 78–80).
Proses AMDAL dipimpin oleh pemohon dan dimulai dengan konsultasi awal dengan para pelaku yang terdampak (Kode Lingkungan, bab 6, s. 28). Secara khusus, sebelum menyusun AMDAL, pemohon harus terlibat dalam konsultasi untuk menentukan cakupan dan detail penilaian yang diperlukan. Konsultasi ini mencakup aspek-aspek seperti lokasi proyek, cakupan, desain, potensi dampak lingkungan, serta konten dan struktur AMDAL (bab 6, s. 29).
Tidak seperti prosedur rencana kerja, yang terutama melibatkan pemilik properti dan pemegang hak yang secara langsung terdampak oleh eksplorasi, konsultasi AMDAL mencakup kelompok peserta yang lebih luas, seperti CAB terkait, Inspektorat Pertambangan, individu yang terdampak, lembaga lain, kotamadya yang terdampak, dan masyarakat umum, termasuk organisasi lingkungan (bab 6, s. 30). Pemohon harus memberikan semua peserta materi yang diperlukan terlebih dahulu, yang merinci jenis konsultasi, spesifikasi proyek, sensitivitas lingkungan, risiko, dan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan (Peraturan Penilaian Dampak Lingkungan, s. 8). CAB memainkan peran penting dalam mengoordinasikan konsultasi, memastikan bahwa EIA memenuhi semua standar yang dipersyaratkan (Environmental Code, bab 6, s. 32).
Ketentuan EIA dalam Environmental Code, seperti prosedur rencana kerja, memberikan kebebasan yang signifikan kepada pemohon dalam menentukan bentuk dan tingkat partisipasi (Environmental Collaboration Sweden 2020). Konsultasi dapat dilakukan secara digital atau tertulis, tanpa persyaratan untuk pertemuan langsung. Namun, pedoman merekomendasikan setidaknya satu sidang langsung di kotamadya tempat penambangan direncanakan dan menyarankan beberapa pertemuan jika memungkinkan. Konsultasi menyeluruh diyakini sebagai kepentingan terbaik pemohon, karena mengurangi kemungkinan permintaan dan banding informasi tambahan, sehingga ketentuan yang lebih ketat tidak diperlukan, menurut pembuat undang-undang (Prop. 2016/17:200, 118).
Setelah konsultasi, pemohon menyiapkan EIA berdasarkan masukan yang diterima (Environmental Code, bab 6, s. 35). AMDAL harus merinci proyek, termasuk lokasinya, kondisi lingkungan, dan dampaknya terhadap aspek-aspek seperti kesehatan manusia, keanekaragaman hayati, tanah, air, udara, iklim, dan warisan budaya. Untuk proyek di daerah penggembalaan rusa kutub Sami, AMDAL juga harus menilai dampak terhadap penggembalaan rusa kutub.5 AMDAL harus menguraikan solusi alternatif, langkah-langkah mitigasi, dan menyertakan laporan konsultasi yang merangkum prosesnya. Pemohon kemudian mengajukan AMDAL ke Inspektorat Pertambangan untuk ditinjau dan dirujuk ke CAB untuk menyeimbangkan kepentingan publiknya.
4.2 Izin Lingkungan
Kode Lingkungan menetapkan persyaratan untuk memperoleh izin lingkungan yang diperlukan untuk pertambangan, termasuk fasilitas pemrosesan dan pengelolaan air, seperti bendungan tailing atau pembuangan air tanah (Kode Lingkungan, bab 11, pasal 3, 9). LEC bertanggung jawab untuk memberikan izin ini (bab 9, pasal 8), yang mengatur kegiatan yang menimbulkan risiko lingkungan yang signifikan untuk memastikan kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan (Kode Lingkungan, bab 1, pasal 1). Masa berlaku izin lingkungan ditentukan dan ditetapkan tergantung pada karakteristik dan keadaan operasi tertentu dan dapat diperpanjang atau diubah jika perlu untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang relevan (Survei Geologi Swedia 2016).
Permohonan izin mencakup deskripsi kegiatan yang diusulkan, EIA, dan tindakan pencegahan serta perlindungan yang sesuai (bab 22). Saat mengevaluasi aplikasi, LEC mempertimbangkan persyaratan perlindungan lingkungan substansial yang diuraikan dalam Kode Lingkungan (bab 2), menilai dampak lingkungan, menetapkan kondisi untuk mengurangi dampak negatif, dan memastikan kepatuhan menyeluruh terhadap ketentuan yang relevan (bab 16, s. 2; bab 22, s. 25; Prop. 1997/98:90, 2, 151).
Proses izin lingkungan menggabungkan unsur-unsur musyawarah terutama melalui persyaratan konsultasi selama pengembangan AMDAL, yang merupakan bagian penting dari aplikasi dan penilaian LEC. Meskipun rincian ketentuan ini dan proses konsultasi telah dibahas di bagian sebelumnya dan tidak akan diulang di sini, penting untuk dicatat bahwa AMDAL dalam proses izin lingkungan lebih komprehensif, mengingat lebih banyak rincian proyek yang tersedia. AMDAL mencakup faktor-faktor seperti transportasi, debu, kebisingan, dan dampak di luar area pertambangan (Kode Lingkungan, bab 6, s. 37), yang memperluas jangkauan aktor yang terkena dampak yang terlibat.
Selain konsultasi EIA, elemen partisipatif mencakup peluang bagi otoritas untuk meninjau aplikasi, meminta rincian, dan bagi para aktor yang terdampak dan publik untuk menyampaikan komentar (pasal 22, bagian 3–4). Sidang utama, yang biasanya terbuka untuk umum, memungkinkan pertanyaan dan komentar, meskipun dapat diabaikan jika tidak diperlukan (pasal 22, bagian 16). Keputusan dapat diajukan banding ke Pengadilan Banding Lingkungan Hidup, dengan banding lebih lanjut ke Mahkamah Agung berdasarkan kondisi tertentu. Kedudukan hukum mencakup para aktor yang terdampak langsung, serta organisasi pekerja dan lingkungan setempat (pasal 16, bagian 1, 12–13).
4.3 Kondisi untuk Musyawarah yang Inklusif, Autentik, dan Berdampak
4.3.1 Kondisi untuk Musyawarah yang Inklusif
Kriteria pertama yang digunakan untuk mengevaluasi desain kelembagaan adalah inklusivitas, yang berfokus terutama pada mekanisme pemilihan peserta dan kemampuan mereka untuk memberikan peluang bagi berbagai aktor yang terdampak, yang mencakup beragam perspektif dan preferensi, untuk berpartisipasi dalam musyawarah.
Undang-Undang Mineral dan Kode Lingkungan mendefinisikan pelaku yang terdampak secara berbeda. Undang-Undang Mineral, khususnya yang mengatur prosedur rencana kerja selama eksplorasi, memiliki cakupan yang lebih sempit, yang memberikan partisipasi kepada pemilik properti dan pemegang hak yang terdampak langsung (Undang-Undang Mineral, bab 17, s. 1). Hal ini mengecualikan pelaku seperti kotamadya, organisasi lingkungan, masyarakat umum, dan non-pemegang hak yang menggunakan lahan. Selain itu, karena dampak kegiatan eksplorasi yang biasanya berskala kecil dan terbatas, jumlah pemegang hak yang dapat berpartisipasi dalam konsultasi rencana kerja sangat dibatasi.
Penentuan apakah tingkat inklusivitas dalam prosedur rencana kerja memadai bergantung pada bagaimana izin eksplorasi dipandang dalam kaitannya dengan potensinya untuk mengarah pada operasi penambangan di masa mendatang. Pembenaran untuk partisipasi terbatas didasarkan pada gagasan bahwa eksplorasi biasanya berskala kecil, terlokalisasi, dan mengakibatkan kerusakan minimal, dengan sedikit kasus yang mengarah pada penambangan yang sebenarnya (Prop. 2004/05:40, 42–43). Namun, konflik dan protes selama tahap eksplorasi sering kali muncul dari persepsi bahwa izin eksplorasi adalah langkah pertama menuju penambangan (Prop. 2004/05:40, 29–30, 50–54). Dari perspektif ini, interpretasi yang lebih luas dari prinsip yang terpengaruh mungkin diperlukan untuk memastikan inklusivitas, termasuk aktor yang mungkin terdampak oleh penambangan di masa mendatang. Mengecualikan aktor-aktor ini dari apa yang mereka lihat sebagai langkah awal menuju proyek pertambangan dapat merusak legitimasi proses dan hasilnya. Kode Lingkungan, yang mengatur AMDAL dan konsultasi terkait dalam proses perizinan pertambangan dan lingkungan, memungkinkan partisipasi yang lebih luas, sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Arahan AMDAL UE dan konvensi seperti Konvensi Espoo (1991) dan Konvensi Aarhus (1998). Kode ini tidak hanya mencakup pemegang hak yang terdampak tetapi juga lembaga terkait, kotamadya, organisasi lingkungan, dan masyarakat luas yang mungkin terdampak oleh proyek (Kode Lingkungan, bab 6, s. 30). Oleh karena itu, ketentuan ini memastikan proses yang lebih inklusif dengan memungkinkan berbagai pelaku yang terdampak untuk berpartisipasi.
Selain mendefinisikan pelaku yang terdampak, aturan yang mengatur bagaimana mereka terlibat dalam musyawarah sangat penting untuk menentukan akses ke proses tersebut. Baik Undang-Undang Mineral maupun Kode Lingkungan Hidup menetapkan tanggung jawab untuk memulai, mengatur, dan melaksanakan konsultasi kepada pemohon (Undang-Undang Mineral, bab 3, s. 5; Kode Lingkungan Hidup, bab 6, ss. 29–32). Hal ini memberikan pemohon keleluasaan yang signifikan dalam aspek-aspek penting, seperti memilih aktor mana yang akan dilibatkan, menentukan waktu dan format konsultasi, memilih tempat, dan mempertimbangkan faktor logistik yang memengaruhi aksesibilitas (Kolaborasi Lingkungan Hidup Swedia 2020). Akibatnya, inklusivitas proses sangat bergantung pada keputusan pemohon, yang menyebabkan variabilitas dan ketidakpastian dalam seberapa efektif berbagai aktor dapat mengakses proses tersebut.
Ketersediaan mekanisme kompensasi bagi peserta merupakan faktor penting lainnya yang memengaruhi inklusivitas dalam proses musyawarah. Baik Undang-Undang Mineral maupun Kode Lingkungan Hidup tidak mengamanatkan penyediaan sumber daya untuk partisipasi, meskipun banyak waktu dan upaya yang diperlukan dari banyak aktor, termasuk persiapan dan advokasi yang ekstensif. Kurangnya dukungan ini dapat menimbulkan hambatan yang substansial, terutama bagi para pelaku yang terpinggirkan dengan sumber daya keuangan yang terbatas, seperti RHC. RHC sering menghadapi tantangan untuk berpartisipasi dalam beberapa konsultasi simultan karena tumpang tindih lahan mereka dengan berbagai kegiatan eksploitasi. Keterlibatan mereka sangat penting ketika proyek direncanakan di lahan mereka, mengingat pemahaman mereka tentang potensi dampak pertambangan. Namun, tidak adanya langkah kompensasi atau sumber daya yang tidak memadai dapat menghambat partisipasi mereka, sehingga mengurangi inklusivitas dan merusak kepentingan serta hak-hak mereka.
4.3.2 Kondisi untuk Musyawarah Otentik
Kriteria kedua yang digunakan untuk menilai desain kelembagaan adalah keaslian, dengan fokus khusus pada sejauh mana komunikasi timbal balik ditentukan antara para pelaku musyawarah dan apakah semua pelaku diberi kesempatan yang sama untuk mengomunikasikan preferensi dan alasan mereka.
Temuan penting adalah bahwa baik Undang-Undang Mineral maupun Kode Lingkungan tidak secara eksplisit mengharuskan pemohon untuk terlibat dalam komunikasi timbal balik selama konsultasi. Sebaliknya, pemohon memiliki keleluasaan untuk menentukan bentuk konsultasi yang paling tepat untuk berbagai pelaku, yang berpotensi mencakup penerimaan pernyataan tertulis sebagai satu-satunya cara komunikasi (Kolaborasi Lingkungan Swedia 2020). Akibatnya, kerangka kelembagaan tidak memastikan standar minimum musyawarah dalam proses ini. Sementara pedoman kebijakan menekankan pentingnya setidaknya satu pertemuan untuk dialog timbal balik (Kolaborasi Lingkungan Swedia 2020; Survei Geologi Swedia 2016), keputusan tentang cara melakukan konsultasi pada akhirnya berada di tangan pemohon, yang menyebabkan variasi dan ketidakpastian dalam bentuk dan kualitas komunikasi dalam proses ini.
Lebih jauh, baik Undang-Undang Mineral maupun Kode Lingkungan tidak secara eksplisit mengamanatkan bahwa konsultasi memiliki fungsi musyawarah, di mana para pelaku dapat dengan bebas menyampaikan klaim dan preferensi mereka dan mempertimbangkannya berdasarkan alasan dan pembenaran. Sebaliknya, konsultasi terutama dibingkai oleh tujuan teknis atau administratif yang diuraikan dalam undang-undang, dengan fokus pada pengumpulan informasi yang diperlukan untuk merencanakan kegiatan eksplorasi atau menentukan ruang lingkup dan detail EIA (Undang-Undang Mineral, bab 3, s. 5; Kode Lingkungan, bab 6, ss. 29–32). Meskipun tidak ada larangan tegas terhadap keterlibatan dalam refleksi terbuka dan pertimbangan preferensi, fokus sempit dari proses ini dapat membatasi kemampuan para pelaku untuk mengomunikasikan kekhawatiran mereka secara efektif atau menawarkan perspektif alternatif yang menantang tujuan pro-pertambangan dari undang-undang tersebut. Akibatnya, beberapa pelaku mungkin menghadapi kendala signifikan dalam mempertimbangkan preferensi dan alasan mereka secara menyeluruh, sehingga membatasi pengembangan musyawarah yang adil.
Undang-Undang Konsultasi Sami menonjol sebagai satu-satunya undang-undang yang secara tegas mengamanatkan konsultasi dengan fungsi musyawarah. Undang-undang ini mengharuskan Inspektorat Pertambangan untuk terlibat dalam konsultasi dengan perwakilan Sami yang relevan sebelum memvalidasi rencana kerja atau membuat keputusan tentang izin pertambangan yang memengaruhi kepentingan atau hak Sami (Undang-Undang Konsultasi Sami, pasal 2, 7). Undang-undang tersebut menekankan pelaksanaan dialog dengan itikad baik, menyajikan posisi yang beralasan dan mempertimbangkan pandangan satu sama lain, yang sejalan dengan norma musyawarah (pasal 9–11). Namun, proses konsultasi ini terbatas pada sekelompok kecil peserta dan tetap tunduk pada ketentuan substantif Undang-Undang Mineral dan Kode Lingkungan. Akibatnya, peserta mungkin masih menghadapi kesempatan terbatas untuk mengungkapkan preferensi atau alasan yang menentang tujuan pro-pertambangan, dan masukan mereka mungkin tidak dipertimbangkan sepenuhnya.
Aspek kelembagaan yang memengaruhi inklusivitas juga secara signifikan memengaruhi apakah para pelaku memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi selama proses konsultasi. Faktor utamanya adalah kewenangan diskresioner yang diberikan kepada pemohon dalam merancang dan memimpin konsultasi (Minerals Act, bab 3, s. 5; Environmental Code, bab 6, ss. 29–32). Kebebasan pemohon untuk menentukan ruang lingkup dan format partisipasi bagi berbagai pelaku berarti bahwa kesetaraan sangat bergantung pada komitmen pemohon terhadap perlakuan yang adil dan memastikan bahwa semua suara didengar secara setara. Selain itu, kurangnya sumber daya yang disediakan untuk partisipasi dapat semakin merusak kesetaraan dalam komunikasi. Biasanya, pemohon—sering kali perusahaan pertambangan—memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya daripada peserta lain, sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang dapat memberi pemohon keuntungan yang tidak adil. Meskipun diyakini bahwa konsultasi yang inklusif dan setara adalah kepentingan terbaik pemohon untuk dilakukan (Kolaborasi Lingkungan Swedia 2020), keinginan untuk mendapatkan persetujuan proyek dapat menyebabkan proses yang bias, di mana sudut pandang tertentu diberikan pertimbangan yang tidak setara atau pernyataan ditafsirkan secara selektif.
4.3.3 Kondisi untuk Musyawarah yang Berdampak
Terakhir, kriteria terakhir untuk mengevaluasi desain kelembagaan sistem adalah konsekuensialitas, yang berfokus pada hubungan antara interaksi musyawarah peserta dan pengambilan keputusan serta sejauh mana hasil musyawarah dapat memengaruhi isi keputusan penting.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, proses konsultasi tidak dirancang untuk menjalankan fungsi musyawarah. Akibatnya, keputusan tidak bertujuan untuk memasukkan hasil yang dihasilkan dari pertukaran preferensi dan alasan secara terbuka. Sebaliknya, keputusan ini terutama bergantung pada penilaian lembaga tentang apakah pelamar telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, adanya konsultasi tidak sama dengan pengambilan keputusan yang berdampak; konsultasi hanya menginformasikan penilaian otoritas dalam batasan kerangka hukum. Hal ini secara signifikan membatasi konsekuensialitas proses ini, termasuk kapasitasnya untuk menantang tujuan kelembagaan tempat proses tersebut beroperasi.
Ketika memeriksa hubungan antara konsultasi dan pengambilan keputusan dalam proses izin eksplorasi, izin pertambangan, dan izin lingkungan, menjadi jelas bahwa proses izin eksplorasi menawarkan potensi paling kecil bagi konsultasi untuk memengaruhi keputusan. Dalam proses ini, konsultasi hanya dilakukan setelah Inspektorat Pertambangan telah menentukan izin eksplorasi. Akibatnya, fokus konsultasi terbatas pada aspek teknis, seperti cara melakukan eksplorasi, tetapi tidak ada peluang konsultasi untuk memengaruhi apakah eksplorasi harus diizinkan (UU Pertambangan, bab 3, pasal 5).
Sebaliknya, proses perizinan pertambangan dan lingkungan melibatkan konsultasi sebelum keputusan perizinan, yang secara teoritis meningkatkan potensi hal tersebut untuk memengaruhi keputusan. Namun, seperti yang dibahas sebelumnya, tujuan dari proses ini bukanlah untuk memprioritaskan dan mempertimbangkan preferensi untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, proses ini berfokus pada penentuan ruang lingkup dan detail EIA, yang menginformasikan penilaian dan keputusan otoritas dalam kerangka hukum (Kode Lingkungan, bab 6, pasal 29–32). Akibatnya, kemampuan proses konsultasi ini untuk memengaruhi keputusan secara signifikan tetap terbatas.
Lebih jauh, beberapa mekanisme dalam hukum dapat melemahkan hubungan antara konsultasi ini dan pengambilan keputusan. Salah satu mekanisme utama adalah keleluasaan yang diberikan kepada pemohon dalam menerjemahkan informasi dari konsultasi ke dalam AMDAL final yang diserahkan kepada pihak berwenang. Hal ini memberikan pemohon kendali yang cukup besar, yang berarti konsekuensi dari proses tersebut sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan pemohon untuk secara akurat mencerminkan hasil konsultasi tanpa bias atau kelalaian, bahkan jika informasi tersebut dapat berdampak negatif terhadap persetujuan proyek.
Mekanisme lain yang dapat melemahkan hubungan ini adalah ketentuan yang memungkinkan Inspektorat Pertambangan untuk mengabaikan penilaian CAB atas kepentingan publik berdasarkan AMDAL (Undang-Undang Mineral, bab 8, s. 2). Dalam kasus seperti itu, masalah tersebut dirujuk ke Pemerintah untuk ditinjau, yang memperkenalkan dimensi politik pada proses pengambilan keputusan. Karena tidak ada opsi untuk mengajukan banding atas keputusan Pemerintah berdasarkan isinya, Pemerintah memiliki kebebasan substansial untuk menyimpang dari AMDAL dan sebagai gantinya menyelaraskan keputusan dengan agenda politik yang berlaku (Undang-Undang 2006:304).
5 Pembahasan
Penerapan demokrasi deliberatif secara luas sebagian besar didorong oleh keyakinan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan pertukaran alasan antara peserta yang bebas dan setara dapat menghasilkan berbagai hasil yang bermanfaat, termasuk manajemen konflik yang efektif (Bächtiger et al. 2018a; Bäckstrand et al. 2010). Namun, meskipun integrasi elemen deliberatif ke dalam sistem tata kelola pertambangan Swedia semakin meningkat, tampaknya sistem ini tidak dapat mencapai janji tersebut. Untuk mengungkap teka-teki ini, studi ini telah meneliti bagaimana musyawarah diterapkan dalam desain kelembagaan sistem, serta menilai sejauh mana desain tersebut menciptakan kondisi untuk musyawarah yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif.
Temuan tersebut mengungkapkan bahwa musyawarah dalam sistem tata kelola terjadi melalui ketentuan yang mengharuskan pemohon izin untuk terlibat dalam dialog dan konsultasi dengan para aktor yang terdampak. Konsultasi ini dimulai selama fase pengembangan rencana kerja eksplorasi, saat pendekatan terhadap aktivitas eksplorasi ditentukan. Selanjutnya, konsultasi memainkan peran penting dalam AMDAL yang dipersyaratkan untuk izin pertambangan dan lingkungan, dengan fokus pada penentuan cakupan dan kedalaman penilaian ini, yang menjadi dasar bagi keputusan otoritas, termasuk peran Badan Pelaksana dalam menyeimbangkan pertambangan dengan kepentingan publik lainnya dan tanggung jawab LEC untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.
Meskipun tidak secara eksplisit disebut musyawarah, proses ini menggabungkan unsur musyawarah dengan memfasilitasi komunikasi antara pemohon izin dan pihak yang terdampak, yang memungkinkan adanya ekspresi pendapat dan pengaruh pada keputusan izin. Konsultasi ini juga berupaya untuk memenuhi tujuan yang selaras dengan literatur musyawarah, seperti mempromosikan pengambilan keputusan yang terinformasi, meningkatkan transparansi, meningkatkan dan memperdalam partisipasi, dan mengelola konflik (Curato et al. 2017; Dryzek dan Niemeyer 2010). Namun, ketika mengevaluasi desain kelembagaan sistem terhadap tiga standar aspirasional demokrasi musyawarah—inklusivitas, keaslian, dan konsekuensialitas (Dryzek 2009)—penilaian tersebut mengungkapkan kekurangan yang signifikan di beberapa area.
Kendala signifikan terhadap inklusivitas muncul dari definisi sempit Undang-Undang Mineral tentang aktor yang terdampak, yang membatasi partisipasi selama tahap eksplorasi hanya kepada pemegang hak yang terdampak langsung. Pendekatan yang mengecualikan ini bermasalah, karena mengecualikan banyak pemangku kepentingan di awal proyek pertambangan, tempat konflik, protes, dan banding sering kali dimulai. Kekuasaan diskresioner pemohon dalam menyelenggarakan konsultasi, termasuk memutuskan waktu, format, logistik, dan kurangnya mekanisme kompensasi bagi peserta, semakin menghambat inklusivitas, membuatnya tidak konsisten dan sangat bergantung pada niat pemohon, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan norma-norma demokrasi.
Kendala terhadap keaslian dalam desain kelembagaan adalah kurangnya persyaratan untuk komunikasi timbal balik selama konsultasi, yang memungkinkan pemohon untuk hanya mengandalkan pernyataan tertulis tanpa memastikan adanya musyawarah. Selain itu, proses-proses ini terutama melayani tujuan teknis dan administratif, dengan fokus pada pengumpulan informasi untuk perencanaan eksplorasi atau pengembangan EIA, daripada memfasilitasi musyawarah di mana para pelaku dapat dengan bebas berbagi dan membenarkan pandangan mereka dan mempertimbangkannya dengan benar. Fokus yang sempit ini membatasi partisipasi yang berarti, terutama bagi mereka yang memiliki masalah di luar tujuan pro-pertambangan undang-undang. Selain itu, kewenangan diskresioner pemohon atas format dan tingkat partisipasi, dikombinasikan dengan tidak adanya mekanisme kompensasi, semakin melemahkan keaslian, membuatnya sangat bervariasi dan bergantung pada komitmen pemohon terhadap keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua aktor yang terdampak untuk didengar.
Terakhir, terkait kepatuhan desain kelembagaan terhadap konsekuensialitas, hambatan muncul dari tidak adanya ketentuan yang mengharuskan keputusan untuk mencerminkan hasil musyawarah, yang dicirikan oleh pertukaran alasan dan preferensi secara terbuka. Selain itu, konsultasi dalam proses perizinan eksplorasi terjadi setelah izin proyek ditentukan, sehingga membatasi pengaruhnya terhadap keputusan perizinan. Selain itu, kewenangan diskresioner pemohon untuk memasukkan informasi konsultasi ke dalam EIA, bersama dengan ketentuan yang memungkinkan Pemerintah untuk melewati penilaian penggunaan lahan CAB untuk menyelaraskan keputusan dengan agenda politik yang berlaku, semakin melemahkan hubungan antara hasil konsultasi dan pengambilan keputusan, sehingga mengurangi konsekuensialitas proses.
Temuan-temuan ini menawarkan wawasan berharga dan penjelasan potensial untuk tantangan sistem dalam mengelola kepentingan yang saling bersaing dan memastikan keputusan yang sah. Temuan-temuan ini menyoroti kesenjangan yang jelas antara keadaan sistem saat ini dan aspirasi demokrasi deliberatif, yang menyajikan gambaran yang lebih selaras dengan skenario ‘bisnis seperti biasa’ daripada transisi menuju sistem tata kelola demokrasi deliberatif yang lebih baik. Temuan-temuan ini konsisten dengan studi empiris sebelumnya tentang tata kelola pertambangan Swedia (misalnya, Fjellborg 2023; Haikola dan Anshelm 2016; Raitio et al. 2020) dan penelitian yang lebih luas tentang tata kelola kolaboratif dan demokrasi partisipatif, yang menekankan bagaimana desain kelembagaan yang ada dapat membatasi praktik-praktik partisipatif, yang mengarah pada proses-proses yang mempertahankan status quo daripada mendorong demokrasi yang lebih dalam (misalnya, Arai et al. 2021; Armeni dan Lee 2021; Baker dan Chapin III 2018; Williams et al. 2022).
Untuk menyelaraskan desain kelembagaan dengan norma-norma demokrasi deliberatif dengan lebih baik, reformasi yang komprehensif sangat penting. Hal ini harus difokuskan pada perluasan definisi aktor yang terdampak, memastikan aturan yang tidak memihak untuk pemilihan dan komunikasi peserta, menyediakan sumber daya atau kompensasi yang memadai untuk partisipasi, mewajibkan komunikasi timbal balik dengan aktor yang terdampak, menetapkan mandat musyawarah yang jelas untuk konsultasi, dan memperkuat hubungan antara hasil konsultasi dan pengambilan keputusan. Menerapkan reformasi semacam itu akan secara signifikan meningkatkan kapasitas musyawarah sistem, menawarkan manfaat normatif yang substansial, dan sangat meningkatkan kemungkinan mewujudkan hasil positif yang terkait dengan demokrasi musyawarah, seperti manajemen konflik yang efektif. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah—dan sejauh mana—hasil positif yang diidentifikasi dalam penelitian musyawarah sebelumnya berlaku untuk konflik yang sulit diatasi dalam situasi dunia nyata (Johansson 2023). Meskipun rekomendasi ini khusus untuk tata kelola pertambangan Swedia, rekomendasi ini dapat menawarkan wawasan berharga untuk mengatasi tantangan serupa dalam sistem yang serupa, sehingga meningkatkan tata kelola musyawarah dalam skala global.
Menyadari peran penting desain kelembagaan, penelitian musyawarah di masa mendatang harus memperluas analisisnya di luar forum individual untuk mempertimbangkan bagaimana struktur kelembagaan tingkat makro memengaruhi kapasitas musyawarah. Meskipun desain kelembagaan sistem tata kelola tidak sepenuhnya mendikte praktik musyawarah dalam sistem tersebut (Sass dan Dryzek 2014), lembaga secara signifikan membentuk hasil politik, terutama ketika tindakan tunduk pada lembaga formal yang ditegakkan oleh otoritas publik dan sanksi formal (Castro 2020; Curato et al. 2019; Raitio 2013; Weber dan Glynn 2006). Oleh karena itu, kecil kemungkinan janji musyawarah akan sepenuhnya terwujud dalam sistem ini atau sistem serupa tanpa perubahan kelembagaan yang substansial. Sekadar terlibat dalam lebih banyak musyawarah dalam desain kelembagaan yang cacat yang gagal membangun kondisi penting untuk musyawarah demokratis tidak mungkin menghasilkan hasil yang efektif.
6 Kesimpulan
Dengan memeriksa dan mengevaluasi elemen-elemen musyawarah dari sistem perizinan pertambangan Swedia, studi ini memberikan wawasan penting tentang demokrasi musyawarah dan tata kelola sumber daya alam. Dengan mengeksplorasi musyawarah di luar forum atau lingkungan eksperimental, penelitian ini menyoroti penerapan demokrasi musyawarah di dunia nyata pada tingkat sistemik, menyoroti tantangan dalam mengintegrasikan solusi musyawarah ke dalam struktur tata kelola yang ada dan menjelaskan mengapa integrasi ini mungkin tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, dengan mengidentifikasi hambatan kelembagaan terhadap musyawarah yang efektif dan mengusulkan reformasi, studi ini menawarkan wawasan penting yang dapat meningkatkan tata kelola sumber daya alam tidak hanya dalam pertambangan Swedia tetapi juga dalam sistem serupa secara global.
Untuk lebih memajukan bidang ini, penelitian di masa mendatang harus mengeksplorasi bagaimana berbagai desain kelembagaan di seluruh sistem politik mendukung atau menghalangi musyawarah yang efektif. Studi perbandingan akan menjadi kunci untuk mengidentifikasi hambatan dan mendorong peningkatan yang inovatif. Seperti yang ditunjukkan, kerangka kerja pengembangan kapasitas musyawarah adalah alat yang efektif untuk analisis tersebut, dan penerapannya yang berkelanjutan dalam penelitian di masa mendatang kemungkinan akan menghasilkan wawasan yang signifikan (Dryzek 2009). Selain itu, menyelidiki praktik musyawarah yang sebenarnya dalam berbagai kerangka kelembagaan sangat penting untuk memperdalam pemahaman kita tentang hubungan antara lembaga tingkat makro dan musyawarah tingkat mikro. Pendekatan ini akan menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana berbagai konfigurasi kelembagaan memengaruhi kualitas dan hasil musyawarah di berbagai sistem. Akhirnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah, dan sejauh mana, hasil musyawarah yang diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya—seperti dalam eksperimen atau publik mini—dapat dicapai dalam konflik yang sulit diatasi dalam situasi dunia nyata.

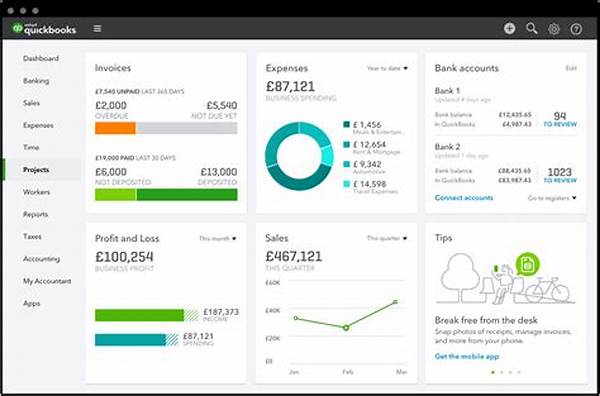


Tinggalkan Balasan